Cinta itu buta. Dulu waktu kecil,
aku kurang begitu mengetahui apa maknanya. Setidaknya itu sampai aku kelas 3
SMP. Karena setelah itu, perlahan-lahan aku mulai mengerti apa maksudnya. Aku
paham.
Paham bahwa cinta itu buta bukan
hanya sekedar pepatah kuno. Sekarang pun, kita bisa melihat fenomena itu
sendiri; seorang pria berwajah buruk rupa bisa menikahi wanita cantik. Mungkin
saja film animasi Beauty and the Beast
itu terinspirasi dari dunia nyata. Siapa yang tahu?
Cinta itu buta. Awalnya, aku hanya
menjadi pengamat saja dari beberapa scene
per scene yang dimainkan oleh
para kerabatku. Aku sering melihat fenomena Beauty
and the Beast itu. Cowok gendut bisa punya pacar seksi. Cewek berkacamata
bisa punya pacar atletis. Dan fenomena itu tak terjadi untuk satu-dua kasus
saja. Dalam setahun, aku bisa melihat lima kasus – bahkan lebih.
Hingga akhirnya, fenomena itu
menghampiri ke kehidupanku. Aku terkena sindrom ‘cinta itu buta’. Aku tak akan
melupakan kapan peristiwa itu terjadi. 12 Mei 2009. Yah itulah tanggal, bulan,
dan tahunnya.
Waktu itu, aku masih seorang
mahasiswa. Mahasiswa Psikologi semester empat. Waktu itu juga, aku mengunjungi
klub malam atau diskotek untuk pertama kalinya – bersama teman-teman
kelompokku. Dosen Psikologi Sosial-ku meminta aku dan keempat teman karibku
untuk ke sana dan mengamati pola kehidupan di sana. Nantinya hasil laporan itu
harus diketikan dalam sebuah paper dengan
minimal sepuluh halaman kertas A4.
Saat itu merupakan kunjungan
pertamaku ke tempat hiburan malam. Maklum aku tipikal anak rumahan. Orangtuaku,
khususnya mama, begitu protektifnya dalam menjaga ketiga anaknya. Waktu aku
memberitahukannya saja, mamaku sampai berulang kali berucap padaku agar aku
tidak coba-coba minum minuman keras ataupun menggunakan obat-obatan terlarang.
Aku sampai capai mendengarnya, kalau kunjunganku ke sana untuk kepentingan
studi. Aku sungguh tak bisa membayangkan, apabila aku tak memberitahukannya
lebih dahulu. Bisa-bisa, saat aku tidak pulang ke rumah pada jam sembilan ke
bawah, mamaku malah akan terus menerus meneleponku, hingga ponselku harus
kumatikan, dan besoknya aku diceramahinya selama kurang lebih satu jam.
Jujur sih, aku ke sana murni
mengobservasi keadaan di sana. Aku sama sekali tak terbawa suasana di sana. Yah
walau sesekali aku juga mencicipi beberapa merek minuman keras yang dipesan
oleh temanku – tapi tak sampai mabuk juga, kok.
Kondisi di klub malam itu – saat aku
ke sana – tak jauh berbeda dengan yang pernah kulihat di film-film. Suara
bising, lampu kedap-kedip, dan di lantai dansanya, banyak orang yang joget
kesetanan tanpa beban. Selain orang-orang yang begitu asyik menari, kulihat
juga ada beberapa orang yang duduk di beberapa bangkunya. Di salah satu bangku
itulah, aku melihat seorang gadis yang sepertinya sebaya denganku, tengah
bermesraan dengan seorang pria yang mungkin sudah sepantasnya menjadi ayahnya.
Saat aku menanyakan perihal gadis
dan om tersebut, temanku, Hanggar bilang padaku bahwa gadis tersebut adalah
seorang pelacur. Sebetulnya aku tak perlu menanyakannya. Momen tersebut sudah
pernah kulihat di film atau sinetron – namun baru kali ini lihat langsung.
Detilnya sih nyaris sama, tapi aku menghindari untuk berburuk sangka.
Gadis dan om itu… atau mungkin
tepatnya, gadis itu… gadis itu seolah menyedot semua warna, garis, dan titik –
hingga di tempat itu, hanya ada aku dan gadis itu. Aku tak tahu kenapa
perhatianku hanya tertuju pada gadis berambut panjang dan berlesung pipi itu. Ada
sesuatu dalam diriku, sehingga aku harus mengunjungi klub malam itu lagi untuk
bertemu gadis nakal tersebut. Aku sampai mendesak teman-temanku untuk mendatangi gadis
itu besok. Aku berdalih, wawancara dengan gadis tersebut juga bermanfaat untuk tugas
kuliah.
“Yah Mas, ada apa yah?” Begitulah
pertanyaan yang ia ajukan padaku saat aku beringsut mendekatinya. Saat itu, ia
sedang duduk sendirian, sambil mengutak-atik
smartphone-nya. Mungkin menghubungi temannya atau… pelanggannya.
“Eeeeh… Kalau boleh tahu, nama mbak
siapa yah?” tanyaku balik.
“Buat apa? Mas mau booking saya memangnya?” Gadis itu
mencoba defensif. Waktu ia berkata seperti itu, aku melihat sebuah senyuman
terindah yang belum pernah kulihat selama ini.
“Hmmm… Bisa dibilang seperti itu.
Tapi bukan booking seperti biasanya.
Saya dan teman-teman saya berniat mewawancarai mbak untuk tugas kuliah. Tuh di
sana,” jawabku, sambil menunjuk ke arah teman-temanku yang berdiri dekat meja
bartender. “Mbak, tenang saja. Karena selain identitasnya bakal disamarkan,
mbak juga akan kami bayar.”
Gadis itu menyimpulkan senyum
terindah itu lagi. Entah kenapa pula, jantungku jadi berdetak-detak kencang.
“Boleh… Jadi kapan? Dan berapa
bayarannya?”
*****
Selanjutnya, acara observasiku dan
teman-temanku berlanjut ke sebuah kamar hotel. Untung saja di kelompokku,
anak-anaknya lumayan tajir. Bukan suatu masalah besar bagi kami, untuk membayar
seorang pelacur dan kamar hotel. Pengorbanan itu juga terbayarkan dengan sebuah
nilai A di Kartu Hasil Studi-ku.
Mungkin saat kita masuk ke kamar
hotel bersama seorang wanita cantik di malam hari, banyak orang mengira ada
apa-apa. Apalagi dia check-in bersama
aku dan keempat temanku. Para karyawan hotel pasti menyangka akan terjadi gangbang. Tapi berani sumpah, gadis nakal itu tidak kami
apa-apakan. Aku dan teman-temanku hanya mewawancarainya. Bukan mewawancarai
juga. Mungkin lebih tepatnya, mengobrol. Yah kata itu lebih sesuai, hingga aku
bisa menemukan kata lain yang lebih pas.
Semenjak pintu kamar dibuka, kami
mempersilakan gadis itu duduk di ranjang hotel, yang dilapisi bed cover. Aku, Hanggar, Rio, Donny, dan
Marco duduk mengitarinya. Tak ada satupun dari kami berlima yang berdiri.
Karena kami menganggap, duduk jauh lebih sopan daripada berdiri. Donny
mengeluarkan blackberry-nya dan
menghidupkan aplikasi recorder-nya.
Lalu gadis itupun mulai bercerita, setelah kami semua mempersilakannya.
Ia mengaku berasal dari provinsi
Sulawesi Utara, tepatnya di kota Tondano. Sama seperti WTS-WTS lainnya, ia
terjerumus ke liang prostitusi ini juga karena faktor keluarga. Ibunya telah
lama meninggal – semenjak melahirkannya. Tinggallah ia bersama ayah dan
abangnya. Ayahnya merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses. Namun saat ia
kelas 11 SMA, tiba-tiba saja ayahnya terkena stroke dan meninggal sebulan
setelah dirawat. Entah bagaimana caranya juga – ia juga bingung, segala harta
kekayaan keluarganya bisa jatuh ke adik ayahnya. Kemudian, tanpa alasan jelas
dan logis, ia dan abangnya diusir pamannya dari rumahnya sendiri. Dengan uang
yang tersisa di dompet, mereka berdua akhirnya mengontrak rumah.
Rupanya masalah yang datang seperti
serangan jantung itu membuat abangnya galau. Pikirannya diserang badai. Abangnya
jadi sering uring-uringan. Sepertinya abangnya belum siap memikul beban yang
begitu besarnya. Sehingga kuliah abangnya jadi berantakan dan memilih drop
out sebulan kemudian. Lebih parahnya lagi, abangnya ikut serta dalam arena
perjudian. Masalah baru datang. Hutang yang begitu besar membuat abangnya nekat
menjual dia ke seorang pengusaha klub malam. Jadilah ia berhenti sekolah,
karena harus terbang ke Jakarta dan menjadi penjaja cinta.
Awalnya dia kikuk dengan kehidupan
barunya itu. Dengan berat hati, ia melakoni pekerjaan barunya. Menemani om-om
minum, diajak check-in ke hotel, dan
melayani nafsu bejat om-om tersebut. Apapun permintaan om-om itu harus ia
lakukan. Jika tidak, uang tak akan didapatkannya dan tubuhnya harus rela
dipukuli oleh seorang germo.
Namun empat bulan setelahnya, ia
mulai menikmatinya. Selain dibanjiri uang tiap malam, ia juga mulai bisa menikmati
setiap permainan seksualnya. Tak hanya soal uang, soal birahi juga menjadi
alasannya kenapa begitu betahnya berkubang dalam liang prostitusi. Ia begitu
menikmati dunia esek-esek itu, sampai sudah melupakan segala hal buruk yang
pernah dialaminya, bahkan termasuk pula melupakan abangnya. Tapi menurut kabar
burung yang ia dengar, abangnya diamankan aparat, karena membunuh pamannya yang
telah mengusirnya.
*****
Setelah check-in di hotel demi tugas kuliah, ada sesuatu yang membuatku
harus terus mengenal gadis kawanua bernama Velita itu. Entah kenapa pula, wajah
cantiknya, tubuh montoknya, hingga penampilan seronoknya terus menjajah
pikiranku. Mungkin cinta telah membuatku buta, sehingga nekat minta nomor
ponselnya dan meneleponnya tiga hari setelah check-in. Urat maluku sepertinya putus. Sadar-tak sadar, aku
mengajaknya untuk makan malam di restoran bintang lima yang ada di ibukota. Awalnya
dia menolak. Namun setelah bujukan dan rayuanku – sekaligus dijanjikan akan
dibelikan sesuatu yang dia mau, dia pun luluh. Sehabis
shopping, aku mengajaknya ke restoran
favoritku untuk makan malam. Di sana, matanya melotot saat mendengar
perkataanku. Aku bilang padanya kalau aku jatuh cinta padanya. Ia menganggapku
hanya becanda saja. Dia bilang, mungkin saja jatuh cinta yang kurasakan adalah
jatuh cinta seorang pelanggan terhadap wanita kupu-kupu malam yang hendak
disewanya. Namun aku meyakinkannya, dengan cara meletakan tangan kanannya di
dadaku. Sambil samar-samar ia mendengar suara detak jantungku, aku menceritakan
setiap keanehan yang kurasakan sejak bertemu dirinya. Tiba-tiba saja matanya
sembap.
Ucapnya dengan mata masih berlinang
air mata, “Kamu tak sepantasnya mencintaiku. Aku wanita jalang. Kotor.
Sedangkan kamu? Kamu anak orang berada. Mahasiswa pula. Kamu pantas mendapatkan
wanita yang lebih baik dariku.”
Aku menjawab, “Kalau boleh memilih,
aku juga inginnya jatuh cinta dengan wanita baik-baik. Tapi hati ini memilih
kamu,” Aku menunjuk-nunjuk dadaku sendiri. “Aku serius. Vel. Aku benar-benar
jatuh cinta sama kamu.”
Dia tak berkata apa-apa lagi. Hanya
menangis, berdiri, dan meninggalkanku tanpa pamit. Bukan tanpa pamit, tapi
kata-kata yang kudengar juga bukann suatu kata-kata yang pantas digunakan untuk
say goodbye. Karena dia berucap,
“Maaf, aku nggak bisa membalas cintamu. Lupakan saja aku.”
Namun aku tidak menyerah begitu
saja. Aku rutin menemuinya di tempat ia biasa mangkal. Dengan dalih mau
mengerjakan tugas bersama teman, aku keluar rumah tiap jam 8-9 malam. Tiap kali
kudekati, ia selalu menjauh. Selalu saja ia membuang mukanya, seolah-olah aku
ini musuh publik nomor satu. Tapi aku tetap menyerah. Aku akan selalu ada di
dekatnya. Tak peduli betapa sakitnya hatiku, saat melihatnya merayu para
pelanggannya.
Untuk pembuktian cintaku padanya ini,
tanpa atau dengan sepengetahuannya aku membantunya. Saat ia butuh uang
transport, aku memberikannya uang. Ia menolak. Namun kudesak, dengan alih-alih
mengatakan bahwa aku hanya meminjamkannya saja. Ia pun mengambil uang itu dari
tanganku dengan sedikit berat. Ia tampak ragu-ragu.
Bahkan saat ia diganggu preman pun,
aku sigap menolongnya. Ia memang seorang pelacur, namun ia tetap seorang
wanita. Ia masih memiliki harga diri seorang wanita yang wajib dibela, walau
hanya secercah saja. Tak sepantasnya ia diperlakukan seperti binatang, hanya
karena statusnya sebagai seorang pelacur. Begitulah nuraniku berbicara – entah
itu memang nurani, atau hanya sekelebat pikiran yang muncul di kala jatuh
cinta.
Cinta itu buta. Cinta telah
membutakan mataku, sehingga rela membiarkan diriku sendiri dalam bahaya demi
seorang yang harga dirinya mungkin lebih rendah. Demi cinta yang buta ini, aku
rela perutku dihujani tinju dari satu-dua preman. Demi cinta pula, mataku harus
lebam. Kalau saja tak ada kamtib yang kebetulan lewat, aku pasti sudah tewas
dan bisa saja, foto diriku ada di salah satu koran besok pagi.
Kamtib itu segera mendatangiku.
Namun orang-orang brengsek itu malah kabur. Dasar pengecut! Lalu samar-samar
kulihat gadis itu, Velita, menghampiriku yang terbaring lemah di trotoar. Ia
memelukku dan berucap, “Preman-preman itu memukuli suami saya, Pak. Entah apa
salah suami saya ini?”
Suami? Tanpa sengaja, di saat aku
sedang sekarat seperti ini, aku malah nyengir. Selama ini kan, ia selalu
menolak kehadiranku di hatinya. Malam ini, ia malah mengakui aku sebagai
suaminya. Hmmm…
Ah, tidak. Sebaiknya aku tidak
terlewat percaya diri dulu. Mungkin saja ia berkata seperti itu sebagai
kamuflase. Ingat, dia seorang pelacur bukan? Mungkin saja ia berkata seperti
itu untuk menghindari ditangkap oleh kamtib-kamtib itu. Perempuan keluyuran di
atas jam 9 malam bukan perempuan yang baik, bukan?
Tapi… Bisa saja kan, karena dia tak
mau melibatkanku dalam masalah yang lebih serius lagi? Dia bisa saja memilih
untuk kabur – sama seperti preman-preman tersebut. Dengan penampilannya yang
begitu seronok, pastilah anggapan kamtib itu sama seperti khalayak ramai:
seorang lelaki hidung belang bersama seorang perempuan nakal. Namun faktanya,
ia tak kabur. Ia malah memilih opsi lain. Opsi memelukku, menganggapku
suaminya, dan ikut mengantarkanku ke sebuah rumah sakit terdekat. Bahkan
samar-samar kudengar, ia juga membayarkan biaya awal pengobatanku. Ia jugalah
yang menghubungi keluargaku, dengan mengutak-atik blackberry yang kutaruh di kantung celanaku.
Aku tak tahu apa maksud dari segala
tindak-tanduknya itu. Namun nuraniku berkata, ia melakukan itu semua bukan
karena kemanusiaan semata. Ia melakukannya karena cinta. Cinta yang murni.
Mungkinkah aku telah berhasil menaklukan hatinya?
Cinta itu buta. Aku tak peduli
anggapan orang lain. Aku tak peduli kecaman orangtua dan keluarga besarku. Aku
juga tak peduli sikap genitnya terhadap banyak lelaki. Karena yang kutahu, aku
harus memperjuangkan cinta ini. Aku harus memperjuangkannya sampai naik
pelaminan.




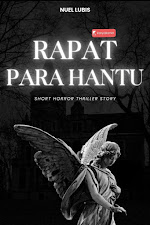

Kepikiran ya bikin ending kayak gitu?! Hebat
ReplyDeleteYang penting ngga berjuang sendirian.. :)
ReplyDelete