Genre: Romance
[GABRIEL KUSTANDI HUTAGALUNG]
"Déjà vu."
Mikha hanya berkata seperti itu saat aku membawanya ke Kota Tua yang sangat bersejarah. Dia tampak terkesan sekali dengan apa yang dilihatnya, seolah-olah ini pengalaman pertamanya. Aku hampir mau tertawa lebar karena ekspresi perempuan kesayanganku ini.
"Kenapa?" tanyaku, dengan mataku tetap terarah ke fokus kamera. Aku kembali beraksi dengan kamera SLR ini. Kamera ini hadiah dari Rafael. Ulang tahun aku yang ketujuh belas itulah kali pertama Rafael memberikanku sesuatu. Aku sebetulnya cukup terkesan saat mengetahui bagaimana Rafael membelikanku kamera. Walau ini kamera murahan, El, tahu tidak, bagiku ini harta paling berharga. Maaf, jika kamu melihatku seperti tak menganggap pemberianmu.
"Ini rasanya seperti déjà vu, Bi," ujar Mikha. "Eh, kamu tahu déjà vu, nggak? Lihat aku dulu, dong. Jangan asyik sendiri mulu sama kamera kamu. Aku banting nanti kameranya."
Aku kembali menatap Mikha. Aku nyengir, dia sewot. Lalu, aku menggeleng. "Déjà vu itu apa, sih? Aku beneren nggak tahu."
"Serius nggak tahu?"
"Sumpah, aku nggak tahu."
"Aku selama ini malah suka anggap kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Kayak pura-pura gitu."
"Apa tampangku kelihatan kayak orang lagi pura-pura? Aku beneren nggak tahu." Maaf, Mikha, kuakui hal itu benar. Aku memang sering merahasiakan sesuatu dari kamu. Banyak sekali. Tentang déjà vu itu, aku tahu apa artinya. Tapi, terkadang kepura-puraan itu jauh lebih mengasyikan. Aku senang dengan rasa antusiasme seseorang akan sisi misterius kita. Juga, aku ingin kamu yang lebih terbuka dulu. Sejak awal aku mengenal kamu, tahukah kamu, justru kamulah sosok misterius tersebut.
"Déjà vu itu pengulangan kejadian, Abi. Itu dari bahasa Perancis. Dan, aku merasa ini bagaikan déjà vu buat aku."
"Maksudnya, kamu pernah ke sini bareng seseorang?" Aku memang sengaja memberikan pertanyaan pancingan seperti itu. Benar, tidak, dugaanku selama ini?
Mikha mengangguk. "Sama Fael. Itu sebulan setelah kita jadi mahasiswa. Habis kelas Hukum Pengantar Hukum Indonesia-nya Pak Max, aku dibawa Fael ke sini. Sebetulnya rada malas, sih. Jarak Atmajaya ke Kota Tua kan lumayan jauh. Udah jauh, waktu itu macet pula. Ditambah lagi, panas."
"Kamu mau bilang, kejadiannya sama persis kayak hari ini? Tadi, pas di Innova aku, kamu ngeluhin macet juga." Aku terbahak.
"Apaan, sih? Nggak ada yang lucu, tauk!" Mikha meradang.
"Bagiku, lucu, Mikha." ucapku tersenyum. "Anyway, aku tahu sebetulnya déjà vu itu apa. Aneh, yah, kenapa harus ada hal kayak gitu? Kenapa Tuhan membiarkan seseorang mengalami hal yang sama untuk kedua kali."
"Hari ini kamu nyebelin, yah, Bi?" gerutu Mikha. Mikha, Mikha, sudah cemburut pun, kamu tetap cantik di mataku. Aku sayang sekali dengan kamu, Mikha!
"Sori."
Mikha beringsut lebih dekat denganku. Dia berbisik, "Bi, aku mau nanya sesuatu, boleh?"
"Tanya apa?" balasku mendesis juga.
"To the point aja, yah," Sontak jantungku berdebar kencang. Jangan bilang Mikha hendak melamarku. "Aku kayaknya paham sama kata-kata kamu pas kita lagi di makam Fael itu. Nggak usah disangkal juga, Bi. Itu hal biasa juga buatku."
Aku menelan ludah. Apa maksudnya ini? Hal-hal seperti itulah yang ingin kutanyakan ke Mikha. Eh, Mikha sudah bertanya lebih dulu.
"Ya udahlah, Bi. Nggak apa-apa. Itu urusan kamu, Fael, dan Tuhan. Aku nggak berhak ikut campur juga." Mikha langsung agak menjauh dariku. "Eh, Bi, fotoin aku, dong, sama artis pantomim yang pake baju tentara Belanda itu. Katanya, kamu jago motret. Coba, buktiin."
Aku terkekeh, lalu mengikuti kemauan Mikha. Mikha yang meminta si artis pantomim untuk mau berfoto bareng. Aku segera pasang aksi. Begitu selesai, Mikha mendatangiku. Dia tampak puas dengan hasil jepretanku.
"Gimana, Tuan Putri? Bagus, nggak? Kalau bagus, aku kirim hasil fotonya ke majalah. Kamu berbakat jadi model. Model majalah fauna, tapi." selorohku. Tawaku meledak. Beberapa pengunjung jadi memperhatikan aku dan Mikha. Mungkin tingkah laku sedikit berlebihan.
"Apaan, sih?!" Mikha ikut tertawa juga. "Eh, aku lapar, nih. Tuh, di sana ada yang jual bakso. Mau nggak?"
Aku mengangguk. Kuikuti Mikha menuju tempat yang berjualan bakso di dekat Museum Fatahillah.
Mikha, terimakasih atas pengertiannya. Maaf juga, untuk sementara ini, aku belum bisa. Mungkin suatu saat nanti, aku dan kamu bisa bebas membicarakan apapun. Aku janji, Mikha, seperti sebuah janji jari kelingking yang anak kecil suka ucapkan.
[MIKHA]
"Déjà vu."
"Ini
rasanya seperti déjà vu, Bi,"
"Eh, kamu tahu déjà vu,
nggak? Lihat aku dulu, dong. Jangan asyik sendiri mulu sama kamera kamu.
Aku banting nanti kameranya."
"Serius nggak tahu?"
"Aku selama ini malah suka anggap kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Kayak pura-pura gitu.
"Déjà vu itu pengulangan kejadian, Abi. Itu dari bahasa Perancis. Dan, aku merasa ini bagaikan déjà vu buat aku."
"Sama Fael. Itu sebulan setelah kita jadi mahasiswa. Habis
kelas Hukum Pengantar Hukum Indonesia-nya Pak Max, aku dibawa Fael ke
sini. Sebetulnya rada malas, sih. Jarak Atmajaya ke Kota Tua kan lumayan
jauh. Udah jauh, waktu itu macet pula. Ditambah lagi, panas."
"Apaan, sih? Nggak ada yang lucu, tauk!" Mikha meradang.
"Hari
ini kamu nyebelin, yah, Bi?"
"Bi, aku mau nanya sesuatu, boleh?"
"To
the point aja, yah,"
"Aku kayaknya paham sama kata-kata kamu pas kita
lagi di makam Fael itu. Nggak usah disangkal juga, Bi. Itu hal biasa
juga buatku."
"Ya
udahlah, Bi. Nggak apa-apa. Itu urusan kamu, Fael, dan Tuhan. Aku nggak
berhak ikut campur juga."
"Eh, Bi,
fotoin aku, dong, sama artis pantomim itu yang pake baju tentara Belanda
itu. Katanya, kamu jago motret. Coba, buktiin."
"Apaan, sih?!"
"Eh, aku lapar, nih. Tuh, di sana ada yang jual bakso. Mau nggak?"
Sederet kenangan tadi siang terbayang-bayang di alam mimpi aku. Tampaknya aku sangat terkesan. Walau tak langsung juga diutarakan oleh Abi, aku amat menghargai Abi. Aku mulai merasa memang kamulah orangnya.
Lalu, perlahan demi perlahan, bayangan itu silih berganti. Terus menerus bergerak cepat. Terus menerus berganti-gantian muncul di hadapanku. Sekarang, muncul di hadapanku satu latar yang sangat aku familier. Aku tidak pernah lupa. Sebab, inilah saat Rafael mencuri ciuman pertamaku. Ada Rafael juga yang berdiri di dekat pohon pinus yang cukup tua usianya. Cengirannya itu menyebalkan.
"Hai, Mikha,"
Aku balas dengan sebuah senyuman.
"Gimana jalan-jalannya sama Abi? Oh iya, aku lupa nanya, apa kalian pernah ciuman bibir?"
Baru aku mau jawab, pemandangannya berubah lagi. Kali ini pemandangan tadi siang, saat aku dan Abi ke Kota Tua. Hanya saja, gedung itu bukanlah gedung Museum Fatahillah yang kukenal. Aku seperti di masa penjajahan Belanda. Kuno sekali di sini. Baru aku hendak berjalan, pemandangannya berubah lagi. Kali ini, aku benar-benar terbangun.
Jam sudah menunjukan pukul empat tiga puluh enam. Apa maksudnya sederetan bayangan di alam mimpiku itu? Aku tak paham. Lalu, kenapa Rafael menanyakan apa aku pernah berciuman bibir dengan Abi?
Di tengah kebingungan aku itu, datanglah SMS dari Abi. Tak biasanya Abi mengucapkan selamat pagi subuh begini. Antara isi SMS Abi dan mimpiku barusan kelihatannya saling berhubungan.
"Morning, My Princess. Nyenyak gak tidur semalam? Kuharap, kamu mimpi indah barusan. Love you so much, and fighting!"
PS:
Cerita
ini hanyalah fiksi belaka yang tak ada kaitannya dengan tempat,
kejadian, atau tokoh apapun. Walaupun demikian, beberapa hal tertentu
dari cerita ini mengacu ke pengalaman aku sendiri.





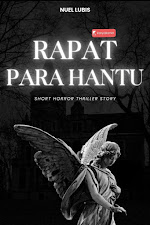

Comments
Post a Comment
Pembaca yang baik adalah yang sudi mau meninggalkan komentar. ^_^
Nice reader is the one who will leave lot of words in the comment box. ^_^